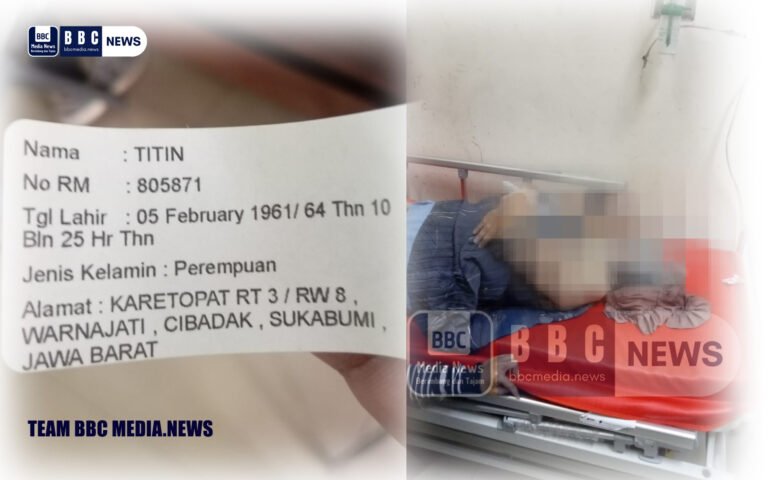BBC MEDIA.NEWS – NTT – Pagi itu, alam Nusa Tenggara Timur seolah ikut berduka. Di sebuah kebun yang jauh dari keramaian, seorang anak berusia 10 tahun ditemukan telah meninggalkan dunia bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, melainkan karena putus asa yang tak pernah semestinya ditanggung oleh anak seusianya.
Ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Usianya belum genap mengenal arti hidup sepenuhnya, namun sudah bersentuhan dengan keputusan paling final: mengakhiri hidup.

Peristiwa ini bukan sekadar tragedi keluarga. Ia adalah luka terbuka bagi bangsa.
// BACA JUGA : LSM ANNAHL SOROTI DUGAAN HIBAH FIKTIF KESRA KABUPATEN SUKABUMI,DESAK APH TURUN TANGAN
Anak yang berinisial Y dikenal pendiam, patuh, dan tidak pernah membuat masalah di sekolah. Ia bukan anak nakal. Ia bukan pembangkang. Ia hanyalah bocah kecil yang ingin belajar, ingin sekolah, ingin menjadi “anak baik” seperti yang sering kita tuntut dari generasi masa depan.
Namun di balik kepolosannya, tersimpan beban yang perlahan menghimpit jiwanya. Keterbatasan ekonomi keluarga, tekanan sekolah, rasa takut mengecewakan orang tua, dan ketidakmampuan mengungkapkan kegelisahan menjadi kombinasi mematikan.
Dalam usia yang seharusnya diisi dengan tawa dan permainan, Y justru memikul kecemasan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya.
Sebelum pergi, ia meninggalkan sepucuk pesan singkat. Bukan amarah. Bukan tudingan. Hanya permintaan maaf dan kalimat yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Kata-kata itu menjadi saksi betapa ia merasa menjadi beban, sebuah perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh dalam diri seorang anak. Dan ini isi surat yang di tinggalkan oleh Y, dalam bahasa daerah Bajawa :
Kertas Tii Mama Reti (Surat untuk mama Reti)
Mama Galo Zee (Mama pelit sekali)
Mama molo Ja’o Galo mata Mae Rita ee Mama (Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis)
Mama jao Galo Mata Mae woe Rita ne’e gae ngao ee (Mama saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya ee)
Molo Mama (Selamat tinggal mama)
// BACA JUGA : GEBRAKAN BUDAYA ! PESULAP MERAH KOLABORASI BERSAMA PRAKTISI DEBUS DADALI PATI SUKABUMI

Di sinilah tragedi ini menjadi lebih dari sekadar berita duka.
Para ahli kesehatan mental menegaskan bahwa anak usia 9–10 tahun memang sudah mulai memahami konsep kematian, tetapi belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola stres, rasa gagal, dan tekanan hidup. Ketika tidak ada ruang aman untuk bercerita—baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan—anak bisa terjebak dalam pikiran hitam-putih: seolah tidak ada jalan keluar selain menghilang.
// BACA JUGA : Warga Dua Desa di Sukabumi Tuntut Pengembalian Sertifikat Tanah yang Disewa Koperasi Bina Usaha ( KBU ) Sejak 2012
Fakta yang lebih memilukan, kasus ini bukan yang pertama. Data perlindungan anak menunjukkan bahwa angka bunuh diri pada anak dan remaja di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap angka adalah satu nyawa. Setiap nyawa adalah satu masa depan yang terhenti.
Ironisnya, semua ini terjadi di tengah jargon pembangunan, anggaran pendidikan triliunan rupiah, dan slogan “anak adalah aset bangsa”. Namun ketika seorang anak tak mampu mendapatkan rasa aman secara psikologis, maka seluruh sistem patut dipertanyakan.
Di mana peran sekolah saat tanda-tanda keputusasaan mulai muncul?
Di mana kehadiran negara ketika kemiskinan membuat pendidikan menjadi beban mental?
Dan di mana kita semua masyarakat, tetangga, aparat desa saat seorang anak mulai menarik diri dalam diam?
Kasus Y adalah tamparan keras bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan kurikulum, seragam, dan bangku sekolah. Anak-anak membutuhkan pendampingan emosional, kepekaan sosial, dan sistem yang benar-benar hadir hingga ke lapisan paling bawah.
Pemerintah daerah hingga pusat perlu berhenti melihat isu ini sebagai “kasus individual”. Ini adalah kegagalan struktural. Kesehatan mental anak harus menjadi prioritas kebijakan publik, bukan sekadar pelengkap program. Sekolah membutuhkan konselor yang aktif, bukan formalitas. Guru perlu pelatihan empati, bukan hanya target akademik. Desa harus menjadi ruang aman, bukan sekadar wilayah administratif.
Lebih dari itu, tragedi ini juga mengetuk kesadaran kita sebagai orang dewasa. Terlalu sering kita menuntut anak untuk kuat, patuh, dan berprestasi, tanpa benar-benar mendengar isi hatinya. Kita lupa bahwa anak-anak tidak selalu mampu berkata, “Aku lelah” atau “Aku takut.”
Ketika seorang anak memilih pergi dalam diam, itu pertanda bahwa teriakannya tak pernah terdengar.
Kini, yang tersisa hanyalah duka dan penyesalan. Namun tragedi ini tidak boleh berlalu sebagai arsip berita semata. Ia harus menjadi pengingat kolektif bahwa setiap anak berhak untuk hidup, bermimpi, dan tumbuh tanpa rasa takut.
Negara boleh membangun jalan, gedung, dan infrastruktur megah. Tetapi jika masih ada anak yang merasa hidupnya tak berharga, maka pembangunan itu kehilangan maknanya.
Karena ukuran kemanusiaan sebuah bangsa bukan dilihat dari tingginya gedung, melainkan dari bagaimana ia menjaga anak-anaknya tetap ingin hidup.
Admin / RR